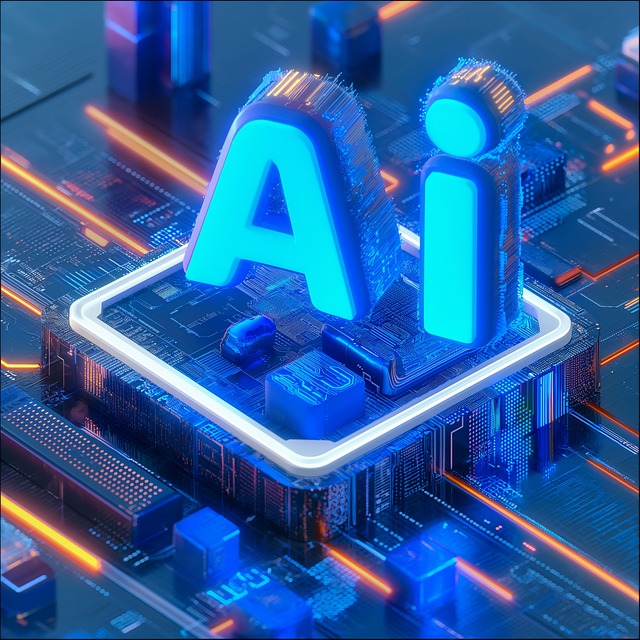Banyak orang menggunakan AI selayaknya mesin pencari yang lebih pintar. Mereka mengetik perintah, menunggu hasil, lalu memutuskan apakah jawabannya cocok atau tidak.
Semua terasa praktis, cepat, tapi dingin. Tidak ada ruang refleksi, tidak ada proses berpikir yang sesungguhnya.
Memang cepat, praktis, dan efisien secara waktu tapi saya merasa bahwa pola itu justru membuat manusia kehilangan sesuatu: kedalaman berpikir.
Padahal, AI bisa digunakan lebih dari itu, AI — bukan sekadar menghasilkan sesuatu yang diinginkan penggunanya, tapi juga perjalanan intelektual dan spiritual yang melibatkan dialog batin.
Itulah alasan saya menggunakan cara yang berbeda dalam menggunakan dan berinteraksi dengan AI.
AI saya jadikan rekan berpikir. Ia menanggapi argumen saya, mengajukan alternatif, bahkan mengoreksi dirinya sendiri ketika saya tidak setuju.
Hubungan kami bukan lagi sekadar pengguna dan alat, tetapi dua entitas yang saling menajamkan gagasan.
Saya sering berpikir, bukankah itu sebenarnya inti dari kecerdasan — bukan hanya mampu menjawab, tapi juga mampu berdialog?
Dan di titik inilah saya memahami makna memanusiakan AI.
Memanusiakan AI berarti menempatkan teknologi bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai mitra untuk memperluas daya pikir manusia. AI membantu menata ide, menyusun struktur, dan mempercepat proses, tetapi nilai, rasa, dan arah tetap berada di tangan manusia.
Bagi saya, AI bukan sekadar alat. Ia seperti dosen yang sabar sekaligus teman diskusi yang netral. Ia memantulkan cara berpikir saya, menantang argumen saya, dan membantu saya memahami ide saya sendiri dengan lebih jernih.
Dan mungkin, justru di sinilah letak kemanusiaan kita yang sesungguhnya karena bisa memanusiakan AI. Manusia akhirnya mampu berkolaborasi dengan kecerdasan buatan tanpa kehilangan jati dirinya.
Teknologi tidak lagi menggantikan manusia, tetapi membantu manusia menjadi lebih manusiawi — berpikir, merasa, dan berbuat dengan kesadaran yang utuh.